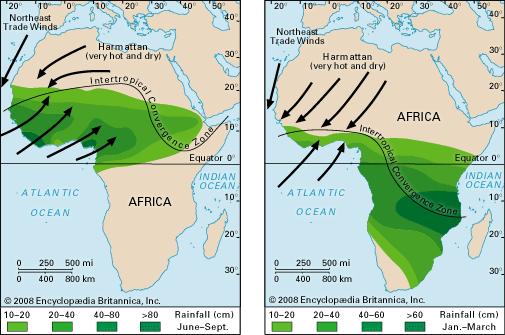Dua
belas tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana alam
tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya dan menelan korban jiwa ratusan ribu
orang. Bencana yang diawali gempa besar di lepas pantai Aceh tersebut dirasakan
dampaknya pada Negara-negara yang berada di seputar samudra Hindia. Suatu
bencana yang sampai sekarang masih menyisakan trauma bagi sebagian masyarakat
Aceh yang mengalaminya. Bahkan siaran langsung yang terus menerus di televisi
nasional bukan tidak mungkin menyebabkan pula trauma bagi masyarakat Indonesia
lainnya yang terpapar oleh berita tersebut.
Indonesia
merupakan Negara yang dilalui oleh sirkum mediterania yang membentang di
Sumatera (Bukit Barisan), Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu dilalui pula
oleh sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi dan Papua. Sirkum Mediterania dan Pasifik ini berupa
barisan pegunungan akibat pertemuan lempeng benua dan samudra di bawahnya.
Seperti diketahui bahwa tumbukan antar lempeng tersebut akan menyebabkan
kemunculan gunung di atasnya. Oleh karena itu wajar bila Indonesia merupakan
wilayah “ring of fire” karena banyaknya gunung api yang terbentuk
sepanjang pertemuan lempeng tersebut.
Tsunami
yang selama ini terjadi biasanya muncul akibat gempa yang terjadi di laut
dengan kedalaman kurang dari 10 km, merupakan akibat dari sesar naik atau
turun, dan gempa yang ditimbulkannya mempunyai amplitude lebih dari 5 skala
Richter. Ketentuan-ketentuan itulah yang selama ini dipakai oleh BMKG dalam
memberikan warning adanya tsunami
atau bukan kepada masyarakat.
Tidak
kalah dahsyatnya adalah pengaruh dari atmosfer di atasnya. Atmosfer di
Indonesia mempunyai perilaku yang unik dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Atmosfer kita mendapatkan tiga pengaruh sirkulasi, yakni yang berarah
meridional (Utara-Selatan) yang disebut sel Hadley, sirkulasi yang berarah
zonal (Barat-Timur) yang disebut sel Walker dan sirkulasi yang sifatnya lokal.
Dalam arah meridional ini kita juga mengenal monsoon, monsun atau muson. Monsun
ini mempunyai pengaruh kuat pada curah hujan di Indonesia khususnya pada
wilayah-wilayah selatan ekuator/khatulistiwa dan sedikit wilayah di Utara
ekuator. Kita mengenal monsun Asia yang
banyak menyebabkan musim hujan di banyak wilayah di tanah air dan monsun
Australia yang membawa pengaruh musim kemarau. Pola hujan selain monsun adalah
pola lokal dan ekuatorial. Pola lokal kebalikan dari pola monsun dimana
biasanya pada bulan-bulan Juni-Juli-Agustus justru curah hujannya tinggi. Pola
lokal bisa juga dicirikan oleh curah hujan sepanjang tahun, hampir dikatakan
tidak ada bulan kering. Pola ekuatorial biasanya terdapat pada wilayah-wilayah
yang terletak di sekitar ekuator. Pola ini mempunyai ciri khas dua kali puncak
musim hujan, yakni sekitar Maret-April-Mei dan September-Oktober-November. Jawa Barat mempunyai pola curah hujan monsun,
dengan demikian maka biasanya pada bulan-bulan Oktober sampai Maret merupakan
musim hujan sedangkan pada bulan April sampai September merupakan musim kemarau.
Puncak kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni-Juli-Agustus.
Pola
monsun yang telah disebut di atas biasanya tidak berpengaruh sendirian. Ada
pengaruh lain yang berskala besar yang turut berperan yakni kejadian di
perairan Indonesia dan sekitarnya. Di perairan Pasifik ekuator ada fenomena
yang dinamakan El Nino dan La Nina, sedangkan di perairan Samudra Hindia
ekuator ada fenomena yang disebut Dipole Mode. Fenomena-fenomena tersebut saat
ini juga sedang berlangsung yakni La Nina (yang diperkirakan akan berlangsung
sampai dengan Pebruari 2017) dan Dipole Mode negatif. Perairan Indonesia yang
juga menghangat juga menyumbang pada besarnya curah hujan di tanah air. Oleh
karena itu tidak heran bahwa akibat meningkatnya curah hujan di tanah air
menyebabkan banjir dan longsor terjadi dimana-mana. Kewaspadaan yang tinggi
harus terus diupayakan agar dampaknya tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
Tanggal
24 Oktober 2016 yang baru lalu, banjir besar melanda Bandung dimana biasanya
wilayah seperti jalan Pasteur dan Pagarsih tidak dilanda banjir semacam itu.
Curah hujan di stasiun pengamat cuaca di Program studi Meteorologi Institut
Teknologi Bandung menunjukkan angka 71 mm/jam. Intensitas hujan sebesar itu
masuk pada kategori sangat sangat deras. Ketika tanggul di Citepus bobol, maka
hujan yang sudah demikian deras ditambah dengan aliran air dari atas yang tidak
mampu ditampung oleh saluran drainase menyebabkan banjir di wilayah-wilayah
yang lebih rendah. Banjir tersebut dalam beberapa waktu kemudian berulang meskipun
tidak sebesar yang pertama.
Banjir
bandang di Garut beberapa bulan yang lalu juga menghancurkan beberapa kawasan
dan menyebabkan hilangnya sebanyak 19 orang. Peristiwa ini juga dipicu oleh
hujan deras yang menimpa bukit-bukit yang sudah gundul/tidak ada tanaman
penguatnya sehingga timbullah banjir bandang. Longsor yang menutupi jalan raya beberapa
waktu yang lalu juga terjadi, misal di antara jalan Tanjungsari menuju Sumedang atau di Bandung barat.
Bencanahidrometeorologis yang lain adalah puting beliung. Puting beliung yang umumnya
disebabkan oleh perbedaan tekanan di beberapa ketinggian dari massa udara
hangat dan dingin yang berlawanan arah menyebabkan pusaran. Pusaran inilah yang
bila terangkat akibat sedotan oleh awan kumulonimbus menyebabkan timbulnya
puting beliung. Di banyak tempat di Jawa Barat hal ini terjadi, dimana beberapa
kali juga menimpa wilayah Bandung baik kabupaten maupun kotamadya. Pada skala
yang lebih besar ada fenomena yang disebut tornado dan siklon. Siklon yang
beberapa waktu ini juga sering terjadi di wilayah sekitar Indonesia sering
membawa dampak pada buruknya cuaca. Hujan deras, petir, atau gelombang besar di
pantai biasanya akibat imbas dari kehadiran siklon di Australia atau di wilayah
Philippina. Siklon di Australia banyak membawa dampak buruk pada
wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Jawa sampai Nusa Tenggara
bagian selatan. Siklon atau topan di Philippina biasanya membawa dampak buruk
pada cuaca dan gelombang di Sulawesi bagian Utara.
Mengingat
bahwa hal-hal di atas tersebut akan terus menerus berlangsung maka sudah
sewajarnya bila masyarakat harus makin dicerdaskan. Hal-hal yang sifatnya
takhayul yang seringkali berhembus ketika suatu peristiwa bencana alam terjadi
harus makin dikikis. Gempa besar, ombak tinggi, tsunami yang terjadi di pantai
Selatan kadangkala dikaitkan dengan kemarahan sang Ratu laut Selatan. Pemahaman
demikian ini harus dihapus agar masyarakat makin rasional dalam menghadapi
sesuatu. Jangan pula bencana di Pidie Jaya Aceh juga diakibatkan oleh ikan lele
raksasa yang menyangga bumi bergerak, seperti sebagian masyarakat tradisional
Jepang yakini. Gerhana bulan atau matahari kadangkala juga diyakini oleh
masyarakat tradisional kita sebagai raksasa yang sedang menelan bulan atau
matahari sehingga perlu dibunyikan kentongan bertalu-talu agar raksasa tidak
memakannya/menghalau raksasa (buta hejo).
Masyarakat harus dididik secara rasional tanpa menghilangkan local wisdom dalam memandang peristiwa
alam dan bencana. Tugas pemerintah melalui instansi atau badan seperti BNPB
(Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BIG (Badan Informasi
Geospasial) dan kementrian terkait lainnya termasuk perguruan tinggi. Kegiatan
mitigasi dan adaptasi harus diupayakan disosialisasikan kepada semua lapisan
masyarakat mulai pada usia dini. Di Jepang misalnya, seseorang yang mengalami
gempa bumi sudah diajarkan sejak kecil untuk berlindung di bawah meja atau lari
keluar mencari tempat yang bebas dari bangunan sekitarnya. Di Negara kita hal
ini belum sampai mencapai taraf semacam itu. Pendidikan kebencanaan sudah
seharusnya didorong oleh pemerintah untuk didirikan minimal di
wilayah-wilayah/propinsi-propinsi yang mempunyai potensi bencana alam baik
darat, laut maupun udara. Jika ini terjadi maka masyarakat akan makin tanggap
bencana dan bisa hidup harmoni dengan alam. Semoga!
Dimuat dalam harian Pikiran Rakyat edisi 4 Januari 2017.